Tokoh – Tokoh Tasawuf
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan
agama yang menghendaki kebersihan lahiriah sekaligus batiniah. Hal ini tampak
misalnya melalui keterkaitan erat antara niat (aspek esoterik) dengan
beragam praktek peribadatan seperti wudhu, shalat dan ritual lainnya (aspek eksoterik).
Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan
perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat
menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Jadi sebagai ilmu sejak awal tasawuf
memang tidak bisa dilepaskan dari tazkiyah al-nafs (penjernihan jiwa).
Upaya inilah yang kemudian diteorisasikan dalam tahapan-tahapan pengendalian
diri dan disiplin-disiplin tertentu dari satu tahap ke tahap berikutnya
sehingga sampai pada suatu tingkatan (maqam) spiritualitas yang diistilahkan
oleh kalangan sufi sebagai syuhud (persaksian), wajd (perjumpaan), atau fana’
(peniadaan diri). Dengan hati yang jernih, menurut perspektif sufistik seseorang
dipercaya akan dapat mengikhlaskan amal peribadatannya dan memelihara perilaku
hidupnya karena mampu merasakan kedekatan dengan Allah yang senantiasa
mengawasi setiap langkah perbuatannya. Jadi pada intinya, pengertian tasawuf
merujuk pada dua hal: (1) penyucian jiwa (tazkiyatun-nafs) dan (2)
pendekatan diri (muraqabah) kepada Allah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Tasawuf
Istilah
"tasawuf"(sufism), yang telah sangat populer digunakan selama
berabad-abad, dan sering dengan bermacam-macam arti, berasal dari tiga huruf
Arab, sha, wau dan fa. Banyak pendapat tentang alasan atas
asalnya dari sha wa fa.[1] Ada yang berpendapat, kata itu berasal dari shafa
yang berarti kesucian. Menurut pendapat lain kata itu berasal dari kata kerja
bahasa Arab safwe yang berarti orang-orang yang terpilih. Makna ini
sering dikutip dalam literatur sufi.[2]
Sebagian
berpendapat bahwa kata itu berasal dari kata Shafwe yang berarti baris
atau deret, yang menunjukkan kaum Muslim awal yang berdiri di baris pertama
dalam shalat atau dalam perang suci. Sebagian lainnya lagi berpendapat bahwa
kata itu berasal dari Shuffa, ini serambi rendah terbuat dari tanah liat
dan sedikit nyembul di atas tanah di luar Mesjid Nabi di Madinah, tempat
orang-orang miskin berhati baik yang mengikuti beliau sering duduk-duduk.[3]
Ada pula yang
menganggap bahwa kata tasawuf berasal dari Shuf yang berarti bulu domba,
yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tertarik pada pengetahuan batin kurang
mempedulikan penampilan lahiriahnya dan sering memakai jubah sederhana yang
terbuat dari bulu domba sepanjang tahun.[4]
B. Bentuk-bentuk Tasawuf Modern
1.
Tasawuf Akhlaqi
Tasawuf
sebagai nomenklatur sebuah perlawanan terhadap budaya materialisme belum ada,
bahkan tidak dibutuhkan. Karena Nabi, para sahabat dan para Tabi'in pada
hakikatnya sudah sufi: sebuah perilaku yang tidak pernah mengagungkan kehidupan
dunia, tapi juga tidak meremehkannya. Selalu ingat pada Allah SWT sebagai sang
Khaliq. Ketika
kekuasaan Islam makin meluas. Ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan,
mulailah orang-orang lalai pada sisi ruhani. Budaya hedonisme pun menjadi
fenomena umum. Saat itulah timbul gerakan tasawuf (sekitar abad 2 Hijriah).
Gerakan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup.
Para
mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa termasuk tasawuf
dan sufi adalah sebuah tema yang muncul setelah abad II Hijriah. Sebuah tema
yang sama sekali baru dalam agama Islam. Pakar sejarah juga sepakat bahwa yang
mula-mula menggunakan istilah ini adalah orang-orang yang berada di kota Bagdad
Irak. Pendapat yang menyatakan bahwa tema tasawuf dan sufi adalah baru serta
terlahir dari kalangan komunitas Bagdad merupakan satu pendapat yang disetujui
oleh mayoritas penulis buku-buku tasawuf[5].
Sebagian
pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakam paham yang sudah berkembang
sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Dan orang-orang Islam baru di daerah
Irak dan Iran (sekitar abad 8 Masehi) yang sebelumnya merupakan orang-orang
yang memeluk agama non Islam atau menganut paham-paham tertentu. Meski sudah
masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari
kemewahan dan kesenangan keduniaan. Hal ini didorong oleh kesungguhannya untuk
mengamalkan ajarannya, yaitu dalam hidupannya sangat berendah-rendah diri dan
berhina-hina diri terhadap Tuhan. Mereka selalu mengenakan pakaian yang pada
waktu itu termasuk pakaian yang sangat sederhana, yaitu pakaian dari kulit domba
yang masih berbulu, sampai akhirnya dikenal sebagai semacam tanda bagi
penganut-penganut paham tersebut. Itulah sebabnya maka pahamnya kemudian
disebut paham sufi, sufisme atau Paham Tasawuf, dan orangnya disebut orang sufi[6].
Dalam
pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang
tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriyah. Oleh karena
itu pada tahap-tahap awal memasuki kehidupan tasawuf, seseorang diharuskan
melakukan amalan dan latihan kerohanian yang cukup berat tujuannya adalah
mengusai hawa nafsu, menekan hawa nafsu, sampai ke titik terendah dan bila
mungkin mematikan hawa nafsu sama sekali oleh karena itu dalam tasawuf akhlaqi
mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut:
1.
Takhalli
Takhalli
merupakan langkah pertama yang harus di lakukan oleh seorang sufi. Takhalli
adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu
dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain
adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi.
2.
Tahalli
Tahalli
adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan
sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi
setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Dengan menjalankan
ketentuan agama baik yang bersifat eksternal (luar) maupun internal (dalam).
Yang disebut aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti
sholat, puasa, haji dan lain-lain. Dan adapun yang bersifat dalam adalah seperti
keimanan, ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan.
3.
Tajalli
Untuk
pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli, maka
rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli
bermakna terungkapnya nur ghaib. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan
organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah
terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur tidak berkurang, maka, rasa
ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan
kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan
menumbuhkan rasa rindu kepada-Nya.[7]
2.
Tasawuf Falsafi
Tasawuf
Falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan (ma’rifat)
dengan pendekatan rasio (filsafat) hingga menuju ketinggkat yang lebih tinggi,
bukan hanya mengenal Tuhan saja (ma’rifatullah) melainkan yang lebih
tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud (kesatuan wujud)[8]. Bisa juga
dikatakan tasawuf filsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran
filsafat. Di dalam tasawuf falsafi metode pendekatannya sangat berbeda dengan
tasawuf sunni atau tasawuf salafi. kalau tasawuf sunni dan salafi lebih
menonjol kepada segi praktis (العملي
), sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis (النطري ) sehingga dalam konsep-konsep tasawuf
falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendektan-pendekatan filosofis
yang ini sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi
orang awam, bahkan bisa dikatakan mustahil[9].
Di dalam
tasawuf falsafi metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau
tasawuf salafi. kalau tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi
praktis (العملي), sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi
teoritis (النطري) sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih
mengedepankan asas rasio dengan pendektan-pendekatan filosofis yang ini sulit
diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi orang awam, bahkan
bisa dikatakan mustahil.[10] Kaum sufi falsafi menganggap bahwasanya tiada sesuatu pun yang wujud
kecuali Allah, sehingga manusia dan alam semesta, semuanya adalah Allah. Dalam
tasawuf falsafi, tentang bersatunya Tuhan dengan makhluknya, setidaknya
terdapat beberapa tema yang telah masyhur beserta para tokohnya yaitu ; hulul,wadah
al-wujud, insan kamil, Wujud Mutlak.
- Hulul
Hulul
merupakan salah satu konsep didalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya
kesatuan antara kholiq dengan makhluk. Paham hululini disusun oleh Al-hallaj. Kata hulul berimplikasi kepada bahwa Tuhan akan menempati dan
memilih tubuh manusia untuk ditempati, bila manusia dapat menghilangkan sifat nasut (kemanusiaannya)
dengan cara fana (menghilangkan sifat-sifat tercela melalui meniadakan alam
duniawi menuju kesadaran ketuhanan).
- Wahdah
Al-Wujud
Istilah
wahdah Al-wujud adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu padu
dengan Tuhan, akan tetapi tuhan disini bukanlah tapi yang dimaksud Tuhan bersatu padu disini bukanlah Dzat yang
Tuhan yang sesungguhnya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia
ketika manusia sudah melakukan proses fana.
- Ittihad
Pembawa
faham ittihad adalah Abu Yazid Al-busthami. Menurutnya manusia adalah pancaran
Nur Ilahi, oleh
karena itu manusia hilang kesadaranya (sebagai
manusia) maka padadasarnya ia telah menemukan asal mula yang
sebenarnya, yaitu nur ilahi atau
dengan kata lain ia menyatu dengan Tuhan.
- Insan
kamil.
- Kesatuan
Mutlak[11]
Corak dari
pada tasawuf falsafi tentunya sangat berbeda dengan tasawuf yang pernah
diamalkan oleh masa sahabat dan tabi’in, karena tasawuf ini muncul karena
pengaruh filasafat Neo-Platonisme.[12]
C. Tokoh – Tokoh Tasawuf
Adapun tokoh-tokoh tasawuf adalah sebagai berikut:
1.
Hamzah
Fansuri
Kiranyanya
namanya di Nusantara, kalangan ulama dan sarjana, penyelidik ke Islaman tidak
asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syeikh Hamzah
Fansuri dan muridnya Syeikh Samsudin Sumatrani adalah tokoh sufi yang sepaham
dengan Al- Hallaj, faham hulul. Ittihad. Mahabbah, dan lain- lain adalah
seirama. Syeikh Hamzah Fansuri diakui salah seorang pujangga islam yang sangat
populer dizamannya, kesustraan melayu dan Indonesia. Namanya tercatat sebagai
tokoh caliber besar dalam perkembangan Islam di nusantara dari abadnya hingga
abad ini. Sufi yang jelas-jelas berpengaruh luar biasa dalam kehidupan
intelektual Al-Fansuri adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Akan tetapi, karya- karya Al-
Fansuri juga menunjukkan bahwa dia akrab dengan ide- ide para sufi, semisal Al-
jilli (wafat 832H/ 1428 M), Aththar
(wafat 618 H/ 1221 M), Rumi (wafat 672 H / 1273 M), dan lain- lain.[13]
2.
Syeikh Yusuf
Makasari.
Seorang tokoh
sufi yang agung yang tiada taranya berasal dari Sulawesi adalah Syeikh Yusuf
Makasari. Beliau dilahirkan pada 08 syawal 1036 H atau bersamaan dengan 03 juli
1629 M, yang berarti belum beberapa lama setelah kedatangan tiga orang penyebar
Islam kesulawesi (yaitu Datok Ribanding dan kawan-kawannya dari Minang kabau).
Untuk diri sebesar ini selain ia dinamakan dengan Muhammad Yusuf diberi gelar
juga dengan “Tuanku Samalaka”, “Abdul Mahasin”, “Hidayatullah” dan lain-lain.
Dalam salah satu karangannya beliau menulis diujung namanya dengan bahasa Arab
“Al- mankasti” yaitu mungkin yang beliau maksudkan adalah “Makassar” yaitu nama
kota disulawesi selatan dimasa pertengahan dan nama kota itu sekarang diganti
pula dengan “ ujung padang “ yaitu mengambil nama yang lebih tua dari pada nama
Makassar. Naluri atau fitrah pribadinya sejak kecil telah menampakkan
diri, cinta akan pengetahuan keislaman, dalam tempo relative singkat,
al-Qur’an 30 juz telah tamat dipelajarinya.
Setelah
lancar benar tentang al-Qur’an dan mungkin beliau termasuk seorang penghafal
maka dilanjutkan pula dengan pengetahuan- pengetahuan lain yang ada hubungannya
dengan itu. Dimulainya dengan ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, kemudian meningkat
hingga ke ilmu bayan, mani’ badi’, balaghah, manthiq, dan sebagainya.
Beriringan dengan ilmu-ilmu yang disebut “ilmu alat” itu beliau belajar pula
ilmu fiqih, ilmu ushulluddin, dan ilmu Tasawuf. Ilmu yang terakhir ini
nampaknya seumpama tanaman yang ditanam ditanah yang subur, kiranya lebih
serasi pada pribadinya. Namun walaupun demikian adanya tiadalah dapat dibantah
bahwa Syeikh Yusuf juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seumpama ilmu
hadits dan sekte-sektenya, juga ilmu tafsir dalam berbagai bentuk dan coraknya,
termasuk ilmu Asbaabun Nuzul, ilmu Tafsir dan sebagainya. Karangan-karangan
syeikh Yusuf Tajul Khawati yang berbahasa Arab mungkin merupakan salinan
tulisan tangan telah diserahkan oleh Haji Muhammad Nur (salah seorang keturunan
khatib di Bone dan mungkin adalah keturunan Syeikh Yusuf sendiri).
Kitab-kitabnya antara lain: Ar- risalatun Nagsabandiyyah, Fathur Rahman,
zubdatul Asraar, asraaris Sharlaah, Tuhfatur Rabbaniyyah, Safinatunnajah,
Tuhfatul labib.[14]
3.
Syeikh Abdul
Rauf As- singkili.
Beliau adalah ulama besar dan tokoh tasawuf
dari Aceh yang pertama kali mengembangkan Thariqat syatariyah di
Indonesia murid-murid beliau menjadi ulama mansyur adalah syeikh Burhanudin
Ulakan R.A, Pariaman Sumatra Barat. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang
berhasil merekonsilialikan (mendamaikan dan menyatukan kembali Syariah dan
tasawuf). Syaikh Abdul Rauf R.A lahir di Aceh tahun 1024 H/ 1615 M. nama
aslinya adalah Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al- jawi Al- fansuri As- singkili.
Beliau lahir disebuah kota kecil ke pantai barat Sumatra. Ayah beliau yaitu
Syeikh Ali Fansuri R.A berasal dari kalangan ulama dan keturunan Arab yang
menikahi seorang wanita setempat dari Fansuri dan bertempat tinggal disingkil.
Syeikh Abdulrrauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1662 M dan setibanya dikampung
mengajarkan dan mengembangkan Thariqat Syataryyah, As- singkili dinilai sebagai
tokoh yang cukup berperan dalam mewarnai sejarah tasawuf diindonesia pada abad
17. Beliau adalah ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali
mengambangkan Tharikat Syatariyah di Indonesia. Murid beliau banyak dan tak
hanya di Aceh saja melainkan dari berbagai penjuru tanah air. Saat Aceh menjadi
tempat persinggahan jama’ah haji yang hendak berangkat ke Mekkah, tidak sedikit
jama’ah haji yang kemudian belajar Agama dan Tasawuf.[15]
BAB III
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan
saran-saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1.
Istilah "tasawuf"(sufism), yang telah
sangat populer digunakan selama berabad-abad, dan sering dengan bermacam-macam
arti, berasal dari tiga huruf Arab, sha, wau dan fa. Banyak
pendapat tentang alasan atas asalnya dari sha wa fa.
2.
Bentuk-bentuk tasawuf modern antar lain tasawuf akhlaqi dan tasawuf falsafi.
3.
Adapun
tokoh-tokoh tasawuf adalah sebagai berikut: Hamzah Fansuri , Syeikh Yusuf
Makasari, Syeikh Abdul Rauf As- singkili.
B. Saran-saran
1. Disarankan kepada umat islam untuk dapat mengamalkan islam sesuai dengan
petunjuk Al – qur’an dan as – Sunnah.
2. Disarankan kepada para mahasiswa/I untuk dapat meningkatkan pembelajaran
tentang kajian Al – Qur’an dan As – Sunnah.
3. Disarankan kepada umat islam untuk berpegang tuguh kepada Al – Qur’an dan
as – Sunnah.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-Quranul Karim
Asmaran As, Pengantar Studi
Tasawuf, Jakarta: Rajawali Pers,
1996.
At-Taftazani, Abu Al-Wafa’
Al-Ghanimi, Madkhal Ila At-Tashawwuf al-Islam, ter. Ahmad Rofi ‘’Utsmani,Sifi
dari Zaman ke zaman’’, Bandung: Pustaka, 1985.
Al-Taftazani, Abu Wafa’
al-Ghanimi, Tasawuf Islam Telaah Historis dan Perkembangannya, Jakarta: GayaMedia Pratama, 2008
Al-Jami, Abd al-Rahman, Nafahat
al-Uns min Hadarat al-Quds:Pancaran Kaum Sufi,
Terj. Kamran As’adIrsyady,ed. Bioer R. Soenardi, Yogyakarta:
Pustaka Sufi, 2003.
Al-Buny, Djamaluddin Ahmad, Mahabbah Tasawuf, Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2002.
Al-Syaibani, Oemar Muhammad At-Tomy, Filsafat Pendidikan Islam ,terj. Hasan Langgulung, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Ali,Fakhry, Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia, Prisma, No. 2 tahun 1983.
Hamka, Tasauf Modern, Jakarta:
Pustaka Panjimas, 1970.
Hamka, Tasauf Perkembangan dan Pemurniannya, Jakarta:
Panjimas, 1993.
Hobby, Kamus Populer,
Cet.XV, Jakarta: Central, 1997.
Harsa, Triyana, Taqdir Manusia Dalam Pandangan Hamka, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
Hamka, Tasawuf Modern, Jakarta: PT
Pustaka Panjimas, 1990.
Hamka, Tasauf Modern,
Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 2005.
Halim,Abdul Mahmud, Tasawuf di Dunia Islam,
Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
[1]Hamka, Tasawuf....., hal. 40.
[8]
Amin Syukur, Menggugat Tasawuf, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56.
[9] Ibid., hal. 57.
[11]Abu
Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Tasawuf Islam Telaah Historis dan
Perkembangannya, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2008), hal. 107-108.

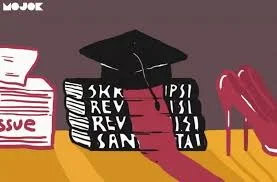
Post a Comment for "Tokoh – Tokoh Tasawuf"