Makna Pengembangan Dayah dan Kepribadian Santri
BAB II
KEDUDUKAN DAYAH DALAM PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN SANTRI
A. Makna
Pengembangan Dayah dan Kepribadian Santri
Secara etimologi kata Dayah diambil dari unsur
bahasa Arab yaitu dari kata zawiyah artinya buju rumah atau buju mesjid.[1]
Buju rumah dimaksudkan dari pengertian ini adalah sudut atau pojok rumah.
Dikatakan sudut atau pojok rumah bahwa pada zaman Rasulullah Saw., pengajaran
dan penerangan tentang ilmu-ilmu agama kepada sahabat dan kaum muslimin sering
beliau lakukan di sudut rumah atau di sudut mesjidnya. Setelah zaman Rasulullah
Saw., kata zawiyah telah berkembang luas ke seluruh pelosok dunia Islam
sampai ke Asia Tenggara. Dari perjalanan sejarah yang panjang kata zawiyah
telah mengalami perubahan dialek sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing.
Di Aceh, kata zawiyah diucapkan dengan sebutan
dayah yang berarti tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dulu, orang Aceh sering
menggunakan sudut, pojok atau serambi rumah dan mesjid untuk mengajarkan
ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dilihat dari persamaan makna dengan daerah
lain di Pulau Jawa, dayah dapat disetarakankan dengan pesantren. Kendatipun
demikian ada beberapa perbedaan yang penting, di antaranya adalah pesantren
merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama,
sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut.[2]
Di samping pengajaran Dayah, juga dipakai
sebagai tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama oleh masyarakat Aceh. Namun
perbedaan antara kedua istilah ini; dayah adalah tempat belajar agama bagi
orang-orang yang telah dewasa. “Sementara pendidikan agama untuk anak-anak
diberikan di Meunasah atau di rumah-rumah guru”.[3]
Ditinjau dari sarana, pendidikan agama tingkat
rendah yang diberikan kepada anak-anak ini dapat dibagi dua bagian. Yang
pertama pendidikan agama untuk anak laki-laki yang mengambil tempat di Meunasah
dan pendidikan agama untuk anak perempuan di rumah-rumah guru atau tempat
khusus. Meskipun demikian materi dan tujuannya sama.
Setelah anak-anak tamat belajar al-Quran dan
telah mampu melaksanakan ibadah wajib, maka tugas terakhir dari pendidikan
Meunasah atau rumah adalah mempelajari kitab agama yang ditulis dalam bahasa
Arab-Jawi (Melayu) seperti Masailal Muhtadi. Tujuan ini memberi bekal bagi
anak-anak yang akan melanjutkan studi lebih lanjut di dayah.
Pendidikan dayah terkenal dengan istilah meuranto
atau meudagang.[4]
Bagi anak-anak Aceh yang mempunyai minat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama
lebih mendalam dapat dilakukan dengan cara meuranto atau meudagang ke berbagai
dayah terkenal. Hal ini dilakukan setelah dia mampu mampu membaca al-Quran dan
memahami cara-cara melakukan ibadah ketika dia belajar di Meunasah atau
di rumah-rumah teungku. Dengan demikian fungsi Meunasah dan dayah akan
sangat bernilai bagi masyarakat Aceh ketika dihubungkan dengan pengajaran
ilmu-ilmu agama.
Dayah berasal dari kata “zawiyah yang
bermakna sudut atau pojok telah berkembang pesat ke seluruh dunia Islam”[5].
Dari semua lembaga pendidikan agama yang berasal dari sudut atau pojok mesjid
tersebut sempat berkembang menjadi Universitas seperti Universitas al-Azhar
Kairo di Mesir. Mula-mula sebelum menjadi sebuah universitas yang besar pengajian
di sudut-sudut mesjid dalam kurun waktu yang lama semakin hari semakin diminati
oleh para kaum muslimin. Dengan demikian sarana belajar yang pertama dipakai di
sudut mesjid ini berubah menjadi Universitas yang mampu menampung banyak santri
di dalamnya. Mulai dari perkembangan ini Azhar University tidak hanya
memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman klasik bahkan juga mengajarkan
teknologi informasi.
Di Aceh, pendidikan dayah telah diperkenalkan
kepada masyarakat sejak beberapa abad sebelum kemerdekaan. Lembaga ini selain
mengajarkan teknik membaca kitab-kitab agama bernuansa klasik yang bahasa Arab
juga mengajarkan nilai-nilai universal dalam bidang pendidikan dan
kemasyarakatan. Di sini telah lahir dan tercipta khas dayah bagi santri yang
pernah mengecap pendidikan dayah yaitu memilki nilai-nilai lokal dan
primordialnya. Nilai-nilai universal adalah nilai-nilai bersifat luas dan
dianggap penting oleh masyarakat di dunia ini. Tetapi nilai-nilai lokal dan
nilai-nilai primordial menurut guru saya, sangat terbatas pada masyarakat
tertentu saja. Dalam konteks ini guru saya mengambil contoh sebuah Universitas
yang asal-usul dari Barat, sekarang sudah diterima secara universal setelah
sifat-sifatnya yang sagat lokal dan primordial dilepaskan. Sebalikanya dayah
yang sudah diterima sebagai lembaga pendidikan yang universal di Asia Tenggara
sejak zaman dulu, saat ini menjadi lembaga lokal yang hanya diminati oleh
masyarakat yang terbatas.
Di era modernisasi dan industrilisasi yang
pernah disebutkan guru saya sebelumnya, sifat-sifat lokal dan primordial akan
menjadi kendala-kendala penting dalam perkembangan masyarakat. Guru saya
melihat indikator ini terjadi pada dayah-dayah yang sangat tradisional yang
membatasi ruang lingkup pelayanannya pada kelompok-kelompok terbatas saja.
Tidak dapat dibantah bahwa lembaga-lembaga pendidikan pada mulanya lahir dari
kebutuhan-kebutuhan terbatas, guru saya memisalkan ini seperti
universitas-universitas di Barat yang pada mulanya lahir dari lingkungan
Gereja. Tetapi lembaga-lembaga ini selanjutnya meluas keluar dari Gereja,
karena di Barat ada sistem pemisahan antara negara dan Gereja. Dari pemisahan
ini menurut guru saya, Universitas berkembang pesat menjadi lembaga yang besar
dan diterima secara universal.
Pendidikan dayah telah mengajarkan ilmu-ilmu
agama melalui telaahan dan bacaan kitab-kitab agama yang bernuansa klasik.
Namun yang terpenting yang harus dimiliki dan diajarkan oleh dayah itu adalah
pendidikan moral. Tanpa moral seorang santri tidak dapat dikatakan ulama walaupun
ia memilki ilmu agama yang hadal. Di sinilah Nabi Muhammad saw., mengingatkan
keberadaan moral melebihi ilmu yang dimilki oleh seseorang. Inti ajaran seperti
inilah yang ditekankan pertama sekali ketika muncul pengajian di sudut-sudut
mesjid yang berasal dari dayah atau zawiyah tersebut.[6]
Pengajaran moral di Dayah mempersiapkan
genersi menjadi seorang ulama yang handal yang mampu mengdapi persoalan umat.
Bahkan tidak sampai di sini, untuk menjadi ulama zaman, harus memahami dan
mempelari pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Sistem ini telah
dirintis dan diterapkan oleh Azhar university yang pertama sekali juga
berangkat dari sudut-sudut mesjid.
Jika terjadi pemisahan antara pendidikan umum
dan pendidikan agama di sebuah lembaga pendidikan kemungkinan besar akan
menjadi seperti nasib Gereja di Barat sebagaimana dijelaskan guru saya
sebelumnya, yakni hanya memikirkan agama sebagai suatu yang terbatas atau yang
primordial. Sedangkan ilmu umum yang lebih mondial diserahkan kepada sekolah
dan universitas-universitas. Bila ini terjadi, guru saya memprediksikan secara
tidak sadar kita akan terjebak dalam ideologi sekuler. Ideologi sekulerisme
memisahkan antara agama dan dunia, dan bila kita ikut menerima pemisahan ini
dengan memberikan pendidikan agama pada dayah dan pendidikan umum pada sekolah
kita pun sebenarnya sudah mengikuti faham sekuler. Jadi orang yang faham
sekuler dalam pandangan guru saya bukanlah yang belajar dunia semata-mata,
tetapi juga belajar agama semata-mata tanpa mengindahkan tanggung jawab dunia.
Kebutuhan masyarakat pada masa yang akan
datang harus dijadikan dasar bagi pendidikan dayah di Aceh yang meliputi moral
dan kebutuhan spritual. Nilai spiritual adalah nilai-nilai yang didapatkan
karena kedekatannya dengan sang Khaliq. Nilai ini sangat berguna bagi penguatan
kepribadian seorang manusia dalam menghadapi berbagai tantangan duniawi menuju
kesejahteraan dan kedamaian bathin.
Kegagalan dalam membina aspek moral dan
spiritual dalam pendidikan akan berefek pada merendahnya kualitas manusia yang
akan dipersiapkan menjadi seorang pendidik atau ulama. Oleh karena itu, dayah
yang berangkat dari sudut-sudut rumah, mesjid atau lanjutan dari pendidikan Meunasah
di Aceh diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam masalah ini. Masyarakat
Aceh ke depan sangat mengharapkan Dayah Meunasah mampu melahirkan
kader-kader ulama yang memiliki pikiran-pikiran bernas dan kapabilitas dalam
menghadapi tantangan global.
Dalam perspektif Islam, istilah kepribadian (personality)
dikenal dengan istilah al-syakhshiyah yang berasal dari kata syakhsh yang
artinya “pribadi”. Kata itu kemudian diberi ya nisbah sehingga menjadi
kata benda buatan (mashdar shina’iy) syakhshiyah yang berarti
“kepribadian”.[7]
Namun dalam literatur keislaman, kata syakhshiyah
kurang begitu dikenal, karena dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak
diketemukan istilah syakhshiyah, kecuali dalam beberapa hadits
disebutkan istilah syakhsh yang berarti pribadi (person), bukan
kepribadian (personality). Para filsuf maupun sufi lebih akrab
menggunakan istilah akhlaq.
Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khulq.
Secara etimologis, akhlak berarti character, disposition dan
moral konstitution. Al Ghazali berpendapat bahwa manusia memiliki citra
lahiriah yang disebut dengan khalq, citra batiniah yang disebut dengan khulq.
Secara etimologi, khulq memiliki arti gambaran atau kondisi kejiwaan
seseorang tanpa melibatkan unsur lahirnya.
Islam membagi akhlak (karakter) menjadi:
pertama, akhlak fitriyah, yaitu pembawaan yang melekat dalam fitrah seseorang,
yang dengannya ia diciptakan, baik sifat fisik maupun sifat jiwa. Kedua, akhlak
muktasabah, yaitu sifat yang semula tidak ada dalam sifat bawaan seseorang,
namun di peroleh melalui lingkungan alam dan sosial, pendidikan, latihan, dan
pengalaman.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa
pada dasarnya manusia sejak lahir telah memiliki kepribadian, dan hal itu
bersifat alami, setelah itu baru lingkungan sosial yang membangun dan
mengarahkan kepribadian tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi manusia
menjadi lebih kuat, melemah, atau mungkin malah tergantikan dengan kepribadian
baru.
Hartati memberi batasan khulq dengan al-thab’u
dan al-sajiyah. Maksud thab’u (karakter) adalah citra batin
manusia yang menetap (al-sukun). Citra ini terdapat pada konstitusi (al-jibillah)
manusia yang diciptakan oleh Allah sejak lahir. Sedangkan sajiyah adalah
kebiasaan (‘adah) manusia yag berasal dari hasil integrasi antara
karekter manusia dengan aktivitas-aktivitas yang diusahakan (al-muktasab).
Kebiasaan ini ada yang teraktualisasi menjadi suatu tingkah laku lahiriah dan
ada juga yang masih terpendam.[8]
Definisi terakhir inilah yang lebih lengkap,
karena khulq mencakup kondisi lahir dan batin manusia. Keinginan, minat,
kecenderungan, dan pikiran manusia ada kalanya terwujud dalam suatu tingkah
laku nyata, dan ada kalanya hanya terpendam di dalam batin dan tidak
teraktualisasi dalam suatu tingkah laku nyata. Berdasarkan uraian ini, khulq
memiliki ekuivalensi makna dengan personality.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat
diambil pengertian bahwa kepribadian adalah merupakan hasil dari proses
sepanjang hidup yang dilalui oleh seseorang yang berbeda-beda dalam menentukan
tingkah laku yang sempurna baik jasmani maupun rohani. Pengembangan kepribadian
itu ditentukan oleh pengetahuan seseorang, sehingga individu dapat menyesuaikan
diri terhadap lingkungannya.
Proses pengembangan yang dialami oleh
seseorang itu berbeda-beda, maka kepribadian tiap-tiap individupun berbeda
antara satu dengan yang lain, sehingga bersifat unik. Tidak ada kepribadian
yang sama antara seorang dengan yang lainnya di dunia ini meskipun saudara
kembar dari satu sel telur.
B. Tujuan
Pengembangan Dayah
Dayah, menurut catatan pakar pendidikan,
merupakan lembaga pendidikan paling awal di Nusantara. Peran dan fungsi dayah
dalam pembelajaran sosial telah menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan
pada masa lalu. Tidak sedikit ulama lahir sebagai hasil pembelajaran dayah yang
berlangsung secara berkesinambungan sampai kini. Dalam konteks Aceh, dayah
tidak saja sebagai pusat pendidikan Islam tetapi juga sebagai pusat dakwah dan
pemberdayaan sosial yang amat penting. Sebagai pusat pendidikan, dayah
merupakan pusat transformasi dan transmisi ilmu dari generasi ke generasi.
Sebagai pusat dakwah, dayah telah menjadi pusat penyiaran agama kepada publik,
sehingga kehadiran dayah benar-benar menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dalam
perkembangannya, dayah juga telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat,
meskipun belum maksimal.
Dalam hal ini Abdul Qadir Djaelani menjelaskan
bahwa:
Dalam kehidupan modern sekalipun dayah belum
kehilangan peran dan fungsinya sebagai wadah atau kajian ilmu meskipun banyak
lembaga pendidikan modern bermunculan. Dayah sebagai pusat pendidikan
tradisional di Aceh masih tetap bertahan tanpa harus menanggalkan
karakteristiknya yang unik. Keunikan pendidikan dayah, yang tetap ada sampai
saat ini, dapat dilihat pada sistem pendidikannya yang konsisten. Fokus
kajiannya adalah teks “Kitab Kuning”, yang berbahasa Arab gundul (tanpa
syakal). Metode pembelajarannya pun unik, yaitu santri menyimak syarahan guru
yang berpedoman pada kitab tertentu; dan terus berlanjut dari satu kitab ke
kitab yang lain. Sistem pendidikan dayah tradisional hampir tidak mengalami
perubahan signifikan dibandingkan dengan sistem pendidikan sekolah atau dayah
terpadu, yang cenderung mengadopsi metode dan perangkat modern. Berdasarkan
kenyataan ini, mungkinkah sistem pendidikan dayah mampu bertahan di era modern,
tanpa mengadaptasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman? Pertanyaan ini akan
dicoba jawab dalam tulisan ini dengan mengemukakan strategi pengembangan,
prospek, dan tantangannya.[9]
Ada dua tradisi dayah yang sudah mengakar
dalam sistem pembelajarannya adalah sebagai berikut:
Pertama, pola pendekatan yang mengembangkan
metode pembelajaran yang lentur dan luwes dalam melakukan transformasi
nilai-nilai keagamaan. Terbukti dalam sejarah, dayah mampu menjadi lembaga
pemersatu dan bersama masyarakat terus bertransformasi. Kedua, tradisi keilmuan yang integral, yaitu
mempelajari suatu ilmu yang saling terkait dengan ilmui-ilmu lain. Tradisi ini
dapat dikembangkan terus sehingga tidak ada lagi dikhotomi ilmu dalam tradisi
keilmuan Islam.[10]
Dengan demikian, Dayah akan menjadi pelopor
Islamisasi ilmu sehingga tidak ditemukan lagi perbedaan atau garis pemisah
antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dan ketiga, arah pendidikan Dayah adalah
tafaqquh fi al-Din sehingga melahirkan ulama-ulama yang handal dalam
berbagai disiplin ilmu. Semangat keilmuan dayah dilandasi semangat keikhlasan,
kesederhanaan, dan kemandirian.
Di era modern, Dayah dapat mengdopsi inovasi
teknologi untuk menopang kualitas pembelajaran. Perangkat teknologi informasi
merupakan sarana paling penting dalam pengembangan sistem pendidikan dayah
zaman kini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral Qur’ani. Memang,
tak dapat dipungkiri bahwa setiap inovasi teknologi pasti melahirkan dampak
ganda, antara manfaat dan mudharat. Di sinilah dayah berperan untuk membuat
filter atau tangkal agar inovasi teknologi dapat memberikan nilai positif dan
konstruktif bagi kehidupan santri dan lingkungan sekitar. Bagaimanapun,
pemanfaatan teknologi pada zaman ini merupakan suatu keniscayaan di mana setiap
orang pasti tidak dapat memisahkan diri darinya. Sebab itu, sebagai subsistem
dunia global, dayah sekurang-kurangnya dapat beradaptasi dengan kemajuan
teknologi tersebut tanpa harus mereduksi nilai-nilai yang dianut selama ini.
Untuk itu, diperlukan kepekaan dan ketajaman analisis dalam mengantsipasi
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum inovasi teknologi
diaplikasikan.
Peran dan fungsi dayah Aceh di masa lampau
tidak sekedar pusat pembelajaran agama bagi masyarakat, melainkan lebih dari
itu. Dayah juga berfungsi sebagai lembaga yang menghasilkan sejumlah alim ulama
para pakar (cendekiawan). Oleh karenanya tak heran pada masa Sultan Iskandar
Muda dan Ratu Safiatuddin bertahta, posisi ulama dalam kontribusinya di bidang
pemerintahan sangatlah penting, yaitu sebagai penasihat bagi para pemimpin yang
sedang menjalankan roda pemerintahan di Aceh.
Seiring dengan berkembangnya kemajuan dimana
umumnya dayah tradisional mulai diperkaya dengan muatan-muatan pengetahuan
umum, maka muncul dua kategori dayah. Pertama disebut dengan dayah modern,
yaitu dayah yang telah dilengkapi dengan sekolah umum dengan jenjang pendidikan tertentu (SMP dan
SMU). Kedua, dayah yang murni hanya mengisi proses pembelajaran yang berpedoman
pada pengajian Alquran, hadist serta beberapa kitab yang ditulis oleh para alim
ulama terdahulu.
Dua model dayah yang ada saat ini mengaju pada
pola pembelajaran tradisional dan pola pembelajaran modern, dimana pola
pembelajaran tradisional mengacu pada pola-pola dan pengetahuan yang telah
dianut oleh generasi terdahulu, sedangkan pola pembelajaran modern memodifikasi
beberapa pengetahuan umum sebagai suplemen bagi pola pembelajaran tradisional.
Adanya dua istilah yang kontras ini, yaitu “tradisional” dan “modern” telah
merangsang pemikiran masyarakat secara umum bahwasanya pola pembelajaran modern
pada suatu dayah lebih baik bila dibandingkan pola pembelajaran tradisional.
C. Metode
Pengembangan Kepribadian
Kepribadian merupakan organisasi dari
faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku
individual. Kepribadian mencangkup kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap, dan
lain-lainnya. Sifat khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila
berhubungan dengan orang lain atau melalui proses belajar terhadap lingkungan
sosial. Kepribadian disebut juga ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang mewakili
sikap atau tabiat seseorang yang mencangkup pola-pola pemikiran dan perasaan,
konsep diri, perangai, mentalitas, yang umumnya sejalan dengan kebiasaan umum.
Dasar-dasar pokok dari perilaku seseorang
adalah faktor-faktor biologis dan faktor-faktor psikologis yang dapat
mempengaruhi pembentukan kepribadian secara langsung, misalnya seseorang
mempunyai cacat fisik dapat mempunyai sifat rendah diri. Faktor psikologis yang
dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian adalah unsur temperamen, perasaan,
keinginan, kemampuan belajar, dan sebagainya. Dengan ditunjang dengan
faktor-faktor sosiologis yaiti sikap berperilaku sesuai dengan keinginan
kelompoknya.
Keinginan setiap individu dalam suatu
masyarakat akan berbeda dengan kepribadian dari kelompok lain. Pembentukan
kepribadian bagi seseorang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tempat
individu tersebut menjadi anggotanya.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh
dalam pengembangan kepribadian adalah :
1. Penanaman
Disiplin Yang Membangun
Perilaku anak dibatasi dengan aturan dan tata tertib tertentu.
Prasyarat aturang untuk membatasi anak haruslah yang: Konsisten (tidak
berubah), Jelas, memperhatikan harga diri anak, beralasan dan dapat dimengerti,
adanya hadiah berupa pujian bila aturan dilaksanakan dengan baik, ada hukuman
jika aturan tidak dilaksanakan, Luwes (tidak kaku), melibatkan anak, tegas, dan
tidak emosional.
2.
Meluangkan
Waktu bersama
3.
Mengembangkan
Sikap Saling Menghargai
4.
Memperhatikan
dan Mendengarkan Pendapat Anak
5.
Membantu
Mengatasi Masalah
6.
Melatih
Anak Mengenal Diri dan Lingkungannya
7.
Mengembangkan
Kemandirian
8.
Memahami
Keterbatasan Anak.
Mengembangkan kepribadian anak dan
mendidiknya merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan oleh orang tua dan
pendidik disekolah dengan tujuan bahwa anak tersebut kelak dapat dan mampu
melakukan hal-hal diluar kemampuan orang lain baik secara individu maupun dalam
sebuah kelompok bahkan dalam sebuah bangsa.
D. Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Pengembangan Kepribadian
Kepribadian itu berkembang dan mengalami
perubahan-perubahan, tetapi di dalam perkembangan makin terbentuklah pola-pola
yang tetap, sehingga merupakan ciri-ciri yang khas dan unik bagi setiap
individu. Menurut Agus Sujanto faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, adalah:
Pertama, Faktor biologis, yaitu yang
berhubungan dengan keadaan jasmani yang meliputi keadaan pencernaan,
pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar urat syaraf, dan lain-lain.
Kedua, Faktor sosial, yaitu masyarakat yakni manusia-manusia lain di sekitar
individu, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang
berlaku dalam masyarakat itu. Ketiga, Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan itu
tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan tentunya kebudayaan dari
tiap-tiap tempat yang berbeda akan berbeda pula kebudayaannya. Perkembangan dan
pembentukan kepribadian dari masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari
kebudayaan masyarakat di mana anak itu dibesarkan.[12]
Sedangkan menurut Singgih D. Gunarsa, faktor-faktor
yang membentuk kepribadian anak ada empat, yaitu: “Pertama, Peranan cinta kasih
dalam pembinaan kepribadian. Kedua, Tidak menghina dan mengurangi hak anak.
Ketiga, Perhatian pada perkembangan kepribadian. Keempat, Menghindari
penggunaan kata kotor”.[13]
Masa kanak-kanak adalah masa yang paling peka
bagi proses pembentukan kepribadian seseorang yang akan mewarnai sikap,
perilaku. dan pandangan hidupnya kelak di kemudian hari. Sedangkan perkembangan
kepribadian anak itu sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu hidup
dan berkembang. Di antara faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi
perkembangan kepribadian anak, adalah orang tua yang mengasuh dan membimbingnya
beserta suasana kehidupan yang dibina. Dalam konteks lingkungan keluarga
inilah, maka kehadiran orang tua akan turut mempengaruhi dan mewarnai proses
pembentukan kepribadian anak selanjutnya.
Menurut Ngalim Purwanto ada beberapa alasan
pentingnya orang tua, terutama ibu dan ayah bagi pembentukan kepribadian anak,
yakni: Pertama, Pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama-tama. Kedua, Pengaruh
yang diterima anak itu batas dan jumlahnya. Ketiga, Intensitas pengaruh itu
tinggi karena berlangsung terus menerus siang dan malam. Keempat, Umumnya
pengaruh itu diterima dalam suasana aman serta bersifat intim dan bernada
emosional.[14]
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
kepribadian anak dipengaruhi oleh banyak factor, dan salah satunya ialah
peranan orang tua dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan memberikan jalan
keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak, karena orang tua
merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak sehingga akan mudah untuk
memahami kepribadiannya.
E. Sarana dan
Prasarana Pendukung dalam Pengembangan
Kepribadian
Secara umum, kepribadian itu pada dasarnya
dibentuk oleh pendidikan, karena pendidikan menanamkan tingkah laku yang
kontinyu dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, ketika ia dijadikan
norma, kebiasaan itu berubah menjadi adat, membentuk sifat, sifat-sifat
seseorang merupakan tabi’at atau watak, tabi’at rohaniah dan sifat lahir
membentuk kepribadian. Hal
ini, sesuai dengan definisi pendidikan, yaitu usaha sadar, teratur, dan
sistematik yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk
mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabi'at sesuai dengan cita-cita
pendidikan. Amir Daien Indrakusuma menegaskan bahwa kepribadian itu dapat
dibentuk oleh pendidikan, dan pendidikan itu sendiri bersumber pada tiga pusat
pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.[15]
Terbentuknya kepribadian pada diri
seseorang, itu berlangsung melalui perkembangan yang terus menerus. Seluruh
perkembangan itu, tampak bahwa tiap perkembangan maju muncul dalam cara-cara
yang kompleks dan tiap perkembangan didahului oleh perkembangan sebelumnya. Ini
berarti, bahwa perkembangan itu tidak
hanya kontiyu, tapi juga perkembangan fase yang satu diikuti dan menghasilkan
perkembangan pada fase berikutnya.
Menurut Ahmad D. Marimba pembentukan
kepribadian merupakan suatu proses yang terdiri atas tiga taraf[16],
yaitu:
1. Pembiasaan
Pembiasaan ialah latihan-latihan
tentang sesuatu supaya menjadi biasa. Pembiasaan hendaknya ditanamkan kepada
anak-anak sejak kecil, sebab pada masa itu merupakan masa yang paling peka bagi
pembentukan kebiasaan. Pembiasaan yang ditanamkan kepada anak-anak, itu harus
disesuaikan dengan perkembangan jiwanya.
Pendidikan yang diberikan kepada anak sejak kecil, merupakan upaya
dalam rangka pembentukan kepribadian yang baik. Hal ini, sebagaimana
dikemukakan oleh M. Athiyah al-Abrasy bahwa para filosof Islam merasakan betapa
pentingnya periode kanak-kanak dalam pendidikan budi pekerti, dan membiasakan
anak-anak kepada tingkah laku yang baik sejak kecilnya. Mereka ini semua
berpendapat bahwa pendidikan anak-anak sejak dari kecilnya harus mendapat
perhatian penuh.[17]
Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, sebagaimana dikutip oleh
M. Athiyah al-Abrasy mengemukakan, bahwa pembentukan yang utama ialah waktu
kecil, maka apabila seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu (yang kurang baik)
dan kemudian telah menjadi kebiasaannya, maka akan sukarlah meluruskannya. Tujuan
utama dari kebiasaan ini, adalah penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan
mengucapkan sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai oleh siterdidik
yang terimplikasi mendalam bagi pembentukan selanjutnya.[18]
2.
Pembentukan minat dan sikap
Dalam taraf kedua ini, pembentukan
lebih dititikberatkan pada perkembangan akal (pikiran, minat, dan sikap atau
pendirian.). Menurut Ahmad D. Marimba bahwa pembentukan pada taraf ini terbagi
dalam tiga bagian[19],
yaitu:
a.
Formil
Pembentukan secara formil,
dilaksanakan dengan latihan secara berpikir, penanaman minat yang kuat, dan
sikap (pendirian) yang tepat. Tujuan dari pembentukan formil ini adalah: Pertama, Terbentuknya cara-cara berpikir yang baik, dapat menggunakan metode
berpikir yang tepat, serta mengambil kesimpulan yang logis. Kedua, Terbentuknya minat yang kuat, yang sejajar dengan terbentuknya
pengertian. Minat merupakan kecenderungan jiwa ke arah sesuatu karena sesuatu
itu mempunyai arti bukan karena terpaksa. Ketiga, Terbentuknya
sikap (pendirian) yang tepat. Sikap terbentuk bersama-sama dengan minat. Sikap
yang tepat, ialah bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap terhadap
agamanya, nilai-nilai yang ada di dalamnya, terhadap nilai-nilai kesulitan, dan
terhadap orang lain yang berpendapat lain.
b.
Materil
Pembentukan materil sebenarnya telah
dimulai sejak masa kanak-kanak, jadi sejak pembentukan taraf pertama, namun
barulah pada taraf kedua ini (masa intelek dan masa sosial). Anak-anak yang
telah cukup besar dan mampu menepis mana yang berguna dan mana yang tidak,
harusnya dilatih berpikir kritis.
c.
Intensil
Pembentukan intensil yaitu
pengarahan, pemberian arah, dan tujuan yang jelas bagi pendidikan Islam, yaitu
terbentuknya kepribadian muslim. Untuk membentuk ke arah mana kepribadian itu
akan dibawa, maka di samping pemberian pengetahuan juga tentang nilai-nilai.
Jadi, bukan hanya merupakan pemberian perlengkapan, tetapi juga pemberian
tujuan ke arah mana perlengkapan itu akan dibawa. Pada segi lain, pembentukan
intensil ini lebih progresif lagi, yaitu nilai-nilai yang mengarahkan sudah
harus dilaksanakan dalam kehidupan. Mungkin masih dengan pengawasan orang tua,
tetapi lebih baik lagi jika atas keinsyafan sendiri.
3.
Pembentukan kerohanian yang luhur
Pada taraf ini, pembentukan
dititikberatkan pada aspek kerohanian untuk mencapai kedewasaan rohaniah, yaitu
dapat memilih, memutuskan, dan berbuat atas dasar kesadaran sendiri dengan
penuh rasa tanggung jawab, kecenderungan ke arah berdiri sendiri yang
diusahakan pada taraf yang lalu, misalnya peralihan dari disiplin luar ke arah
disiplin sendiri, dari menerima teladan ke arah mencari teladan, pada taraf ini
diintensifkan.
Berdasarkan hal tersebut di atas,
dapat disimpulkan bahwa yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga, baik
dalam bentuk bimbingan, pendidikan, maupun perhatian merupakan salah satu upaya
yang dapat membentuk kepribadian anak. Selain itu, terdapat pula cara lain yang
dapat dipergunakan dalam membentuk kepribadian, yaitu pembiasaan, yang
bertujuan untuk menanamkan kecakapan-kecakapan berbuat, mengucapkan sesuatu
dengan tepat, dan dapat dikuasai oleh si anak serta mempunyai implikasi yang
mendalam bagi pembentukan kepribadian pada tahap selanjutnya.
[2]
Abdurrahman Saleh, dkk, Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren,
Proyek Pembinaan Bantuan Kependidikan Pondok Pesantren, 1984/1985, (Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI), hal. 11.
[4]
Safwan Idris, Refleksi Pewaris Nilai-Nilai Budaya Aceh, Peta Pendidikan Dulu
dan Sekarang, (Ar-Raniry, No. 73, 1998), hal. 58.
[7] Netty
Hartati, et al. Islam dan Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 124.
[9] Abdul
Qadir Djaelani, Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan PolitikIslam di
Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 33.
[10]
Ahmad Muthohar, AR, Ideologi Pendidikan Pesantren, Pesantren ditengah Arus
Ideologi-Ideologi Pendidikan, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2007), hal. 22.
[13] Singgih
D. Gunarsa, Psikologi Praktik Anak, Remaja dan Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 2000), hal. 112.
[16] Ahmad
D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Cet. Ke. VIII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989), hal. 88.
[17] M.
Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 105-107.

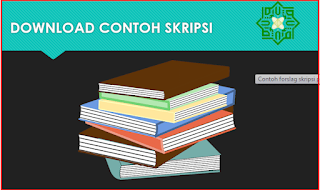
Post a Comment for "Makna Pengembangan Dayah dan Kepribadian Santri"